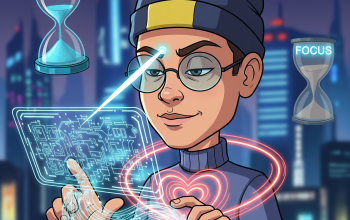Jakarta, CITRAMEDIA – Hujan turun sejak sore, pelan tapi sabar, seperti sedang menghitung dosa yang belum dibayar.
Malam itu, tanah di belakang rumah Siti menyerah. Tidak dengan suara gemuruh besar, hanya bunyi retak yang cukup untuk memisahkan hidup menjadi sebelum dan sesudah.
Pagi harinya, Siti berdiri di depan puing rumahnya.
Kalender masih menempel di potongan dinding, tanggalnya berhenti.
Seolah waktu ikut terkubur bersama dapur kecil tempat ia biasa menanak nasi.
“Yang penting selamat,” katanya lirih.
Kalimat yang terlalu sering diucapkan korban bencana, bukan karena mereka ikhlas, tapi karena tak punya pilihan lain.
Di pos pengungsian, anak-anak tidur beralaskan tikar.
Tas sekolah mereka masih berdebu.
Pelajaran hari itu bukan matematika atau bahasa, melainkan kata-kata baru: longsor, bantuan, relokasi.

Trauma masuk kurikulum tanpa pernah mereka daftar.
Di sudut lain, seorang kakek duduk memandangi sepatu botnya yang penuh lumpur. Kebunnya hilang.
Puluhan tahun kerja keras disapu dalam satu malam.
Baginya, longsor bukan berita, ia adalah akhir dari harga diri dan rutinitas.
Namun di luar tenda pengungsian, kita sering mendengar kalimat lain yang jauh lebih dingin:
Ini bencana alam.
Kalimat itu diucapkan seolah tak ada tangan manusia di baliknya.
Seolah hutan yang hilang menebang dirinya sendiri.
Seolah izin tambang dan alih fungsi lahan muncul tanpa tanda tangan.
Padahal alam tidak pernah mendadak kejam. Ia hanya jujur setelah terlalu lama diabaikan.
Longsor dan banjir bukan takdir yang jatuh dari langit. Ia adalah keputusan yang disahkan di ruang ber-AC, di atas meja rapat, jauh dari rumah-rumah yang akan runtuh.

Negeri ini rajin merayakan pembangunan, tapi malas menghitung ongkos kemanusiaannya.
Grafik ekonomi naik, sementara rumah warga turun ke jurang. Investasi dipuji, korban diminta mengerti.
Ketika bencana datang, negara hadir dengan baliho empati dan pidato penghiburan.
Namun sebelum itu, saat alam diperingatkan oleh data, oleh kajian, oleh jeritan warga, kehadiran sering berubah menjadi pembiaran.
Korban lalu disebut “terdampak”.
Satu kata yang rapi, tapi terlalu sempit untuk menampung kehilangan:
kehilangan rumah, kehilangan rasa aman,
kehilangan kepercayaan.
Ironisnya, di tengah lumpur dan duka, manusia justru saling menemukan.
Warga memasak bersama.
Relawan datang tanpa diminta.
Solidaritas tumbuh dari reruntuhan.
Rakyat sering kali lebih cepat hadir daripada kebijakan.
Bencana ini bukan sekadar soal hujan ekstrem atau perubahan iklim.
Ini soal sistem yang membiarkan alam dijadikan korban kedua setelah manusia.
Soal hukum yang berani pada yang lemah, tapi gemetar di hadapan modal.
Soal pembangunan yang lupa bertanya: siapa yang menanggung risikonya?
Aktivisme lingkungan bukan urusan segelintir orang yang mencintai pohon.
Ia adalah perjuangan untuk hak hidup yang layak.
Untuk rumah yang tak runtuh saat hujan.
Untuk anak-anak yang belajar di sekolah, bukan di tenda pengungsian.
Jika hari ini kita masih menyebut ini sebagai takdir, maka longsor berikutnya adalah persetujuan diam-diam.
Jika kita memilih lupa setelah berita berlalu, maka banjir selanjutnya hanyalah pengulangan.
Siti dan ribuan korban lain tidak butuh belas kasihan semata. Mereka butuh keberanian negara untuk mengubah arah.
Untuk berhenti berdamai dengan kerusakan.
Untuk menempatkan keselamatan di atas keuntungan. Karena alam tidak pernah meminta lebih. Ia hanya ingin dihormati.
Dan ketika peringatan lembut tak lagi didengar, ia berbicara dengan cara yang paling menyakitkan.
Pertanyaannya kini sederhana, tapi menentukan: apakah kita akan terus menyangkal, atau akhirnya belajar sebelum semuanya benar-benar runtuh?